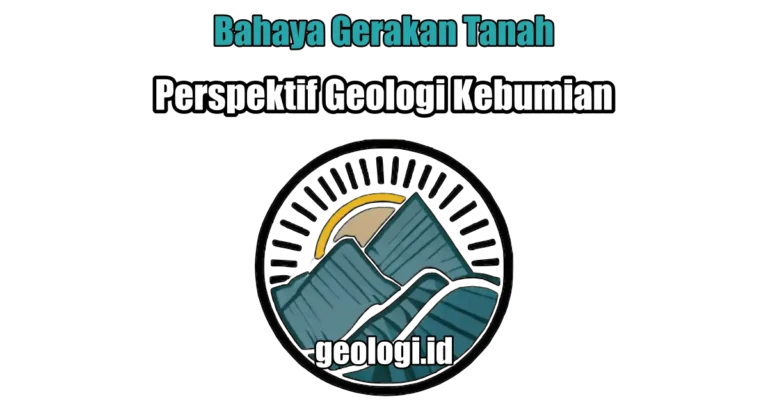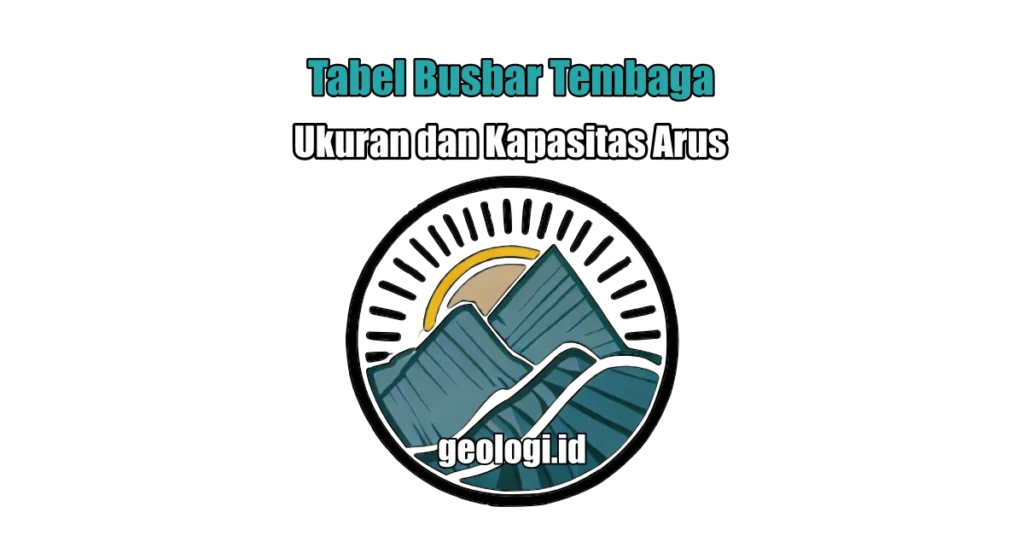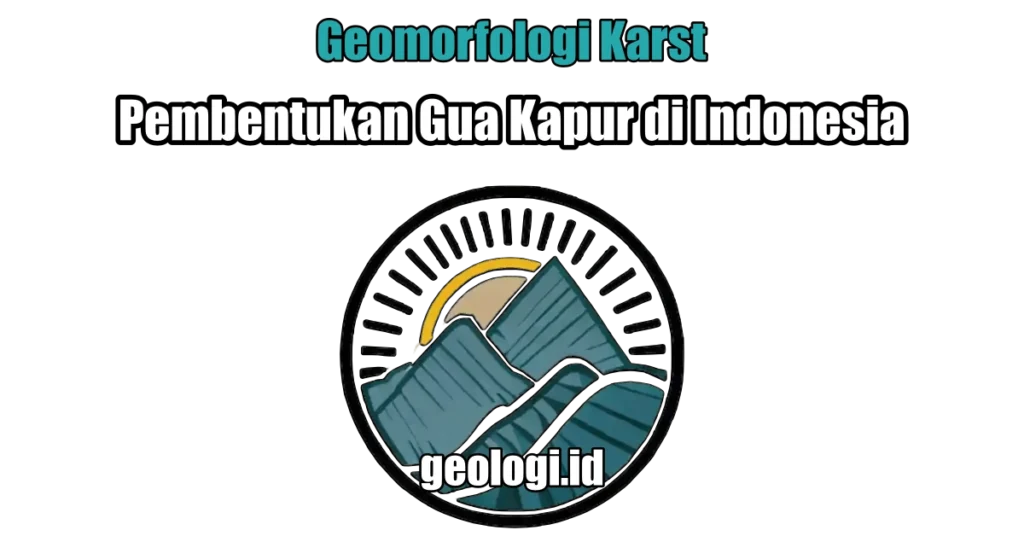Halo, sobat geologi! Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini, saya mau ngobrol-ngobrol tentang salah satu bahaya geologi yang sering kita dengar atau bahkan alami di Indonesia, yaitu gerakan tanah. Apa sih gerakan tanah itu? Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa dampaknya bagi kita? Bagaimana cara mengenali dan mengatasinya? Yuk, simak ulasan saya berikut ini.
Pendahuluan
Gerakan tanah adalah proses perpindahan massa batuan atau tanah akibat gaya berat. Gerakan tanah bisa terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, tergantung pada faktor-faktor penyebabnya. Gerakan tanah merupakan bahaya geologi yang cukup sering terjadi di Indonesia, karena kondisi geologi dan lingkungan yang mendukung terjadinya proses ini.
Beberapa contoh bencana gerakan tanah yang pernah terjadi di Indonesia antara lain adalah longsoran di Banjarnegara pada tahun 2014 yang menewaskan 105 orang, aliran lumpur di Sidoarjo pada tahun 2006 yang menyebabkan ribuan rumah tenggelam, dan erupsi gunung api di Merapi pada tahun 2010 yang memicu lahar dingin. Bencana-bencana ini menunjukkan betapa besar dampak gerakan tanah bagi kehidupan manusia dan lingkungan.
Tujuan artikel ini adalah untuk membahas tentang bahaya gerakan tanah dari perspektif geologi kebumian, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur, komposisi, dan dinamika bumi. Artikel ini juga akan menjelaskan faktor-faktor penyebab, tipe-tipe, dan dampak dari gerakan tanah serta cara mengenali dan memitigasi bahaya tersebut.
Faktor Penyebab Gerakan Tanah
Faktor penyebab gerakan tanah dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi daerah, seperti jenis batuan, struktur geologi, bidang gelincir, dan pelapukan. Faktor eksternal adalah faktor yang berkaitan dengan kondisi lingkungan, seperti kelerengan, tutupan lahan, curah hujan, gempa bumi, dan erupsi gunung api.
Faktor Internal
Faktor internal merupakan faktor yang bersifat intrinsik atau bawaan dari daerah yang rawan gerakan tanah. Faktor internal ini dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas massa batuan atau tanah yang berpotensi bergerak. Berikut ini adalah beberapa faktor internal yang perlu kita ketahui:
- Jenis batuan: Jenis batuan dapat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik massa batuan atau tanah. Jenis batuan yang lunak, rapuh, atau tidak kompak cenderung lebih mudah bergerak daripada jenis batuan yang keras, kuat, atau padat. Contohnya adalah batuan sedimen seperti pasir, lempung, atau lanau yang lebih rentan terhadap gerakan tanah daripada batuan beku seperti granit atau basalt.
- Struktur geologi: Struktur geologi adalah susunan atau pola dari massa batuan atau tanah. Struktur geologi dapat mempengaruhi arah dan bentuk dari gerakan tanah. Contohnya adalah patahan (retakan), lipatan (lengkungan), sesar (pergeseran), atau foliasi (lapisan) yang dapat menjadi jalur atau bidang gelincir bagi massa batuan atau tanah.
- Bidang gelincir: Bidang gelincir adalah bidang permukaan antara massa batuan atau tanah yang bergerak dengan massa batuan atau tanah yang tetap. Bidang gelincir dapat berupa bidang struktural (seperti patahan, sesar, atau foliasi) atau bidang non-struktural (seperti permukaan tanah, batas lapisan, atau kontak batuan). Bidang gelincir dapat mempengaruhi tipe dan kecepatan dari gerakan tanah.
- Pelapukan: Pelapukan adalah proses perubahan fisik atau kimia dari massa batuan atau tanah akibat pengaruh atmosfer, hidrosfer, atau biosfer. Pelapukan dapat menurunkan kekuatan dan stabilitas massa batuan atau tanah. Contohnya adalah pelapukan fisik yang menyebabkan retakan-retakan pada batuan atau pelapukan kimia yang menyebabkan perubahan mineral pada batuan.
Faktor Eksternal
Faktor eksternal merupakan faktor yang bersifat ekstrinsik atau datang dari luar daerah yang rawan gerakan tanah. Faktor eksternal ini dapat memicu atau mempercepat terjadinya gerakan tanah. Berikut ini adalah beberapa faktor eksternal yang perlu kita ketahui:
- Kelerengan: Kelerengan adalah sudut kemiringan dari massa batuan atau tanah. Kelerengan dapat mempengaruhi gaya berat dan gaya gesek yang bekerja pada massa batuan atau tanah. Semakin besar kelerengan, semakin besar pula gaya berat dan semakin kecil gaya gesek. Hal ini dapat meningkatkan potensi terjadinya gerakan tanah.
- Tutupan lahan: Tutupan lahan adalah jenis dan luasnya vegetasi yang menutupi permukaan tanah. Tutupan lahan dapat mempengaruhi keseimbangan air dan tanah pada massa batuan atau tanah. Tutupan lahan yang baik, seperti hutan, dapat menyerap air hujan, mengurangi erosi, dan meningkatkan koheksi tanah. Tutupan lahan yang buruk, seperti lahan terbuka, dapat meningkatkan aliran permukaan, mempercepat pelapukan, dan menurunkan kekuatan tanah.
- Curah hujan: Curah hujan adalah jumlah air hujan yang jatuh pada suatu daerah dalam suatu periode waktu. Curah hujan dapat mempengaruhi kadar air dan tekanan pori pada massa batuan atau tanah. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan kadar air dan tekanan pori pada massa batuan atau tanah. Hal ini dapat menurunkan kekuatan dan stabilitas massa batuan atau tanah.
- Gempa bumi: Gempa bumi adalah getaran atau goncangan bumi akibat pelepasan energi dari pergerakan lempeng tektonik. Gempa bumi dapat mempengaruhi gaya inersia dan gaya dinamik yang bekerja pada massa batuan atau tanah. Gempa bumi yang kuat dapat mengalahkan gaya gesek dan gaya kohesi yang menahan massa batuan atau tanah. Hal ini dapat menyebabkan gerakan tanah secara tiba-tiba.
- Erupsi gunung api: Erupsi gunung api adalah keluarnya material vulkanik (seperti lava, abu, gas, atau batu) dari dalam bumi melalui gunung api. Erupsi gunung api dapat mempengaruhi beban dan suhu pada massa batuan atau tanah. Erupsi gunung api yang besar dapat menambah beban dan meningkatkan suhu pada massa batuan atau tanah. Hal ini dapat menyebabkan perubahan sifat fisik dan mekanik massa batuan atau tanah.
Tipe Gerakan Tanah
Tipe gerakan tanah dapat dibedakan berdasarkan bentuk bidang gelincir yang terbentuk, yaitu longsoran bidang (plane failure), longsoran baji (wedge failure), toppling failure, dan circular failure. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing tipe gerakan tanah:
Longsoran Bidang
Longsoran bidang adalah gerakan tanah yang terjadi pada bidang gelincir yang datar atau sedikit miring. Longsoran bidang biasanya terjadi pada batuan yang memiliki struktur lapisan (seperti batu pasir, batu gamping, atau batu lempung) atau pada kontak antara batuan yang berbeda (seperti batuan beku dan batuan sedimen). Longsoran bidang biasanya bergerak dengan kecepatan rendah hingga sedang. Contoh lokasi di Indonesia yang pernah mengalami longsoran bidang adalah di Gunung Kelud, Jawa Timur pada tahun 2014.

Longsoran Baji
Longsoran baji adalah gerakan tanah yang terjadi pada bidang gelincir yang membentuk sudut tajam. Longsoran baji biasanya terjadi pada batuan yang memiliki struktur patahan atau sesar (seperti batuan metamorf atau batuan beku). Longsoran baji biasanya bergerak dengan kecepatan sedang hingga tinggi. Contoh lokasi di Indonesia yang pernah mengalami longsoran baji adalah di Gunung Salak, Jawa Barat pada tahun 2012.

Toppling Failure
Toppling failure adalah gerakan tanah yang terjadi pada bidang gelincir yang membentuk sudut negatif. Toppling failure biasanya terjadi pada batuan yang memiliki struktur lipatan atau foliasi (seperti batuan metamorf atau batuan sedimen). Toppling failure biasanya bergerak dengan kecepatan rendah hingga sedang. Contoh lokasi di Indonesia yang pernah mengalami toppling failure adalah di Gunung Sibayak, Sumatera Utara pada tahun 2018.

Circular Failure
Circular failure adalah gerakan tanah yang terjadi pada bidang gelincir yang membentuk lengkungan. Circular failure biasanya terjadi pada tanah yang memiliki kohesi rendah atau nol (seperti tanah pasir, tanah lempung, atau tanah organik). Circular failure biasanya bergerak dengan kecepatan rendah hingga tinggi. Contoh lokasi di Indonesia yang pernah mengalami circular failure adalah di Banjarnegara, Jawa Tengah pada tahun 2014.

Dampak Gerakan Tanah
Dampak gerakan tanah dapat bersifat fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berikut ini adalah beberapa dampak gerakan tanah yang perlu kita ketahui:
Dampak Fisik
Dampak fisik adalah dampak yang berkaitan dengan kerusakan atau perubahan fisik dari infrastruktur, morfologi, atau transportasi akibat gerakan tanah. Beberapa contoh dampak fisik antara lain adalah:
- Kerusakan infrastruktur: Gerakan tanah dapat merusak infrastruktur seperti rumah, jalan, jembatan, saluran irigasi, pipa air, kabel listrik, atau fasilitas publik lainnya. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu fungsi dan layanan dari infrastruktur tersebut bagi masyarakat.
- Perubahan morfologi: Gerakan tanah dapat mengubah morfologi atau bentuk permukaan bumi. Perubahan morfologi dapat menciptakan bentuk baru seperti bukit, lembah, danau, atau sungai. Perubahan morfologi juga dapat menghilangkan bentuk lama seperti gunung, pulau, pantai, atau hutan.
- Gangguan transportasi: Gerakan tanah dapat mengganggu transportasi baik darat, laut, maupun udara. Gangguan transportasi dapat disebabkan oleh penutupan jalan, longsor ke sungai atau laut, atau abu vulkanik di udara. Gangguan transportasi dapat menghambat mobilitas dan aksesibilitas masyarakat.
Dampak Sosial
Dampak sosial adalah dampak yang berkaitan dengan kesejahteraan atau kualitas hidup manusia akibat gerakan tanah. Beberapa contoh dampak sosial antara lain adalah:
- Korban jiwa: Gerakan tanah dapat menyebabkan korban jiwa baik meninggal, luka-luka, hilang, atau cacat. Korban jiwa dapat disebabkan oleh tertimbun, terseret, terjatuh, terbakar, atau tercekik massa batuan atau tanah. Korban jiwa dapat menimbulkan duka dan trauma bagi keluarga dan masyarakat.
- Pengungsian: Gerakan tanah dapat menyebabkan pengungsian masyarakat dari daerah yang terdampak. Pengungsian dapat disebabkan oleh kerusakan rumah, ancaman bahaya, atau kekurangan sumber daya. Pengungsian dapat menimbulkan masalah kesehatan, keamanan, pendidikan, atau sosial bagi pengungsi.
- Trauma: Gerakan tanah dapat menyebabkan trauma psikologis bagi masyarakat yang mengalami atau menyaksikan bencana. Trauma dapat disebabkan oleh ketakutan, kesedihan, marah, bersalah, atau stres. Trauma dapat menurunkan kesehatan mental, motivasi, atau produktivitas masyarakat.
Dampak Ekonomi
Dampak ekonomi adalah dampak yang berkaitan dengan kerugian atau biaya finansial akibat gerakan tanah. Beberapa contoh dampak ekonomi antara lain adalah:
- Kerugian materiil: Gerakan tanah dapat menyebabkan kerugian materiil bagi masyarakat atau pemerintah. Kerugian materiil dapat disebabkan oleh kerusakan atau kehilangan harta benda, seperti rumah, kendaraan, ternak, tanaman, atau barang-barang lainnya. Kerugian materiil dapat menurunkan kekayaan atau kesejahteraan masyarakat.
- Penurunan produktivitas: Gerakan tanah dapat menyebabkan penurunan produktivitas bagi masyarakat atau pemerintah. Penurunan produktivitas dapat disebabkan oleh gangguan aktivitas ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, atau jasa. Penurunan produktivitas dapat menurunkan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- Biaya rehabilitasi: Gerakan tanah dapat menyebabkan biaya rehabilitasi bagi masyarakat atau pemerintah. Biaya rehabilitasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki atau memulihkan kondisi daerah yang terdampak. Biaya rehabilitasi dapat mencakup biaya perbaikan infrastruktur, relokasi masyarakat, rekonstruksi rumah, atau rehabilitasi lingkungan.
Dampak Lingkungan
Dampak lingkungan adalah dampak yang berkaitan dengan kerusakan atau perubahan lingkungan akibat gerakan tanah. Beberapa contoh dampak lingkungan antara lain adalah:
- Erosi tanah: Gerakan tanah dapat menyebabkan erosi tanah, yaitu hilangnya lapisan atas tanah akibat angin, air, atau gravitasi. Erosi tanah dapat menurunkan kesuburan tanah, mengurangi vegetasi, atau meningkatkan sedimentasi sungai.
- Sedimentasi sungai: Gerakan tanah dapat menyebabkan sedimentasi sungai, yaitu penumpukan material erosi di dasar sungai. Sedimentasi sungai dapat mengubah aliran sungai, mengurangi kedalaman sungai, atau menyumbat saluran sungai.
- Polusi air: Gerakan tanah dapat menyebabkan polusi air, yaitu pencemaran air oleh material berbahaya seperti lumpur, abu, gas, atau zat kimia. Polusi air dapat menurunkan kualitas air, mengganggu ekosistem air, atau membahayakan kesehatan manusia.
Cara Mengenali dan Memitigasi Bahaya Gerakan Tanah
Cara mengenali bahaya gerakan tanah dapat dilakukan dengan melakukan pemetaan zonasi kerentanan gerakan tanah berdasarkan parameter geologi dan lingkungan. Pemetaan zonasi kerentanan gerakan tanah adalah proses pembuatan peta yang menunjukkan tingkat kerentanan suatu daerah terhadap gerakan tanah. Peta zonasi kerentanan gerakan tanah dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pengelolaan dan mitigasi bahaya gerakan tanah.
Berikut ini adalah contoh peta zonasi kerentanan gerakan tanah di Indonesia dan kriteria-kriterianya:

| Zona | Warna | Kriteria |
|---|---|---|
| Sangat Rendah | Hijau Muda | Kelerengan < 8%, Curah Hujan < 2000 mm/tahun, Jenis Batuan Keras |
| Rendah | Hijau Tua | Kelerengan 8-15%, Curah Hujan 2000-3000 mm/tahun, Jenis Batuan Sedang |
| Sedang | Kuning | Kelerengan 15-25%, Curah Hujan 3000-4000 mm/tahun, Jenis Batuan Lunak |
| Tinggi | Oranye | Kelerengan 25-35%, Curah Hujan > 4000 mm/tahun, Jenis Batuan Rapuh |
| Sangat Tinggi | Merah | Kelerengan > 35%, Curah Hujan > 4000 mm/tahun, Jenis Batuan Pelapukan |
Cara memitigasi bahaya gerakan tanah dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang masing-masing cara memitigasi bahaya gerakan tanah:
Pencegahan
Pencegahan adalah cara memitigasi bahaya gerakan tanah yang dilakukan dengan mengurangi faktor-faktor penyebab gerakan tanah. Beberapa contoh kegiatan pencegahan antara lain adalah:
- Reboisasi: Reboisasi adalah penanaman kembali pohon-pohon di daerah yang mengalami kerusakan hutan. Reboisasi dapat meningkatkan tutupan lahan, menyerap air hujan, mengurangi erosi, dan meningkatkan koheksi tanah.
- Stabilisasi lereng: Stabilisasi lereng adalah penguatan atau pengamanan lereng yang rawan gerakan tanah. Stabilisasi lereng dapat dilakukan dengan cara fisik (seperti pengeboran, pengikatan, penggalian, atau penimbunan) atau biologis (seperti penanaman rumput, semak, atau pohon).
- Pengaturan tata guna lahan: Pengaturan tata guna lahan adalah penetapan atau pengawasan penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan keterbatasan daerah. Pengaturan tata guna lahan dapat mencegah penggunaan lahan yang tidak sesuai, seperti pembangunan di daerah rawan gerakan tanah.
Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan adalah cara memitigasi bahaya gerakan tanah yang dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan masyarakat menghadapi bencana. Beberapa contoh kegiatan kesiapsiagaan antara lain adalah:
- Pembuatan sistem peringatan dini: Sistem peringatan dini adalah sistem yang dapat mendeteksi atau memprediksi terjadinya gerakan tanah dan memberikan informasi atau sinyal kepada masyarakat. Sistem peringatan dini dapat berupa alat teknologi (seperti sensor, radar, atau satelit) atau metode tradisional (seperti bunyi, warna, atau bau).
- Penyuluhan masyarakat: Penyuluhan masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau keterampilan kepada masyarakat tentang bahaya dan mitigasi gerakan tanah. Penyuluhan masyarakat dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, edukasi, atau simulasi.
- Simulasi evakuasi: Simulasi evakuasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk melatih masyarakat dalam melakukan evakuasi saat terjadi bencana. Simulasi evakuasi dapat dilakukan dengan cara mengadakan latihan rutin, menyiapkan jalur evakuasi, menentukan titik kumpul, atau menyediakan perlengkapan evakuasi.
Tanggap Darurat
Tanggap darurat adalah cara memitigasi bahaya gerakan tanah yang dilakukan dengan memberikan bantuan atau pertolongan kepada korban atau daerah yang terdampak. Beberapa contoh kegiatan tanggap darurat antara lain adalah:
- Penyelamatan korban: Penyelamatan korban adalah kegiatan yang bertujuan untuk mencari, mengevakuasi, atau menyelamatkan korban yang terjebak atau terisolir akibat gerakan tanah. Penyelamatan korban dapat dilakukan dengan cara manual (seperti menggali, mengangkat, atau menarik) atau mekanis (seperti menggunakan alat berat, helikopter, atau perahu).
- Penanganan medis: Penanganan medis adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan perawatan atau pengobatan kepada korban yang mengalami luka-luka, sakit, atau trauma akibat gerakan tanah. Penanganan medis dapat dilakukan dengan cara memberikan pertolongan pertama, mengirimkan ke rumah sakit, atau mendirikan posko kesehatan.
- Distribusi bantuan: Distribusi bantuan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan dasar atau dukungan kepada korban atau daerah yang terdampak. Distribusi bantuan dapat dilakukan dengan cara mengirimkan makanan, minuman, pakaian, selimut, tenda, atau obat-obatan.
Pemulihan
Pemulihan adalah cara memitigasi bahaya gerakan tanah yang dilakukan dengan memperbaiki atau memulihkan kondisi daerah yang terdampak. Beberapa contoh kegiatan pemulihan antara lain adalah:
- Relokasi masyarakat: Relokasi masyarakat adalah kegiatan yang bertujuan untuk memindahkan masyarakat dari daerah yang rawan atau terdampak gerakan tanah ke daerah yang aman atau baru. Relokasi masyarakat dapat dilakukan dengan cara memberikan lahan, rumah, atau fasilitas baru kepada masyarakat.
- Rekonstruksi infrastruktur: Rekonstruksi infrastruktur adalah kegiatan yang bertujuan untuk membangun kembali infrastruktur yang rusak atau hilang akibat gerakan tanah. Rekonstruksi infrastruktur dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi, merenovasi, atau membangun baru infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran irigasi, pipa air, kabel listrik, atau fasilitas publik lainnya.
- Rehabilitasi lingkungan: Rehabilitasi lingkungan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan lingkungan yang rusak atau berubah akibat gerakan tanah. Rehabilitasi lingkungan dapat dilakukan dengan cara menanam kembali pohon-pohon, membersihkan sungai atau laut, atau mengembalikan fungsi ekosistem.
Penutup
Demikianlah ulasan saya tentang bahaya gerakan tanah dari perspektif geologi kebumian. Semoga artikel ini dapat memberikan informasi dan wawasan yang berguna bagi anda. Gerakan tanah adalah bahaya geologi yang tidak bisa dihindari, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama peduli dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi bahaya gerakan tanah di Indonesia.
Sekian dan terima kasih.
Salam geologi