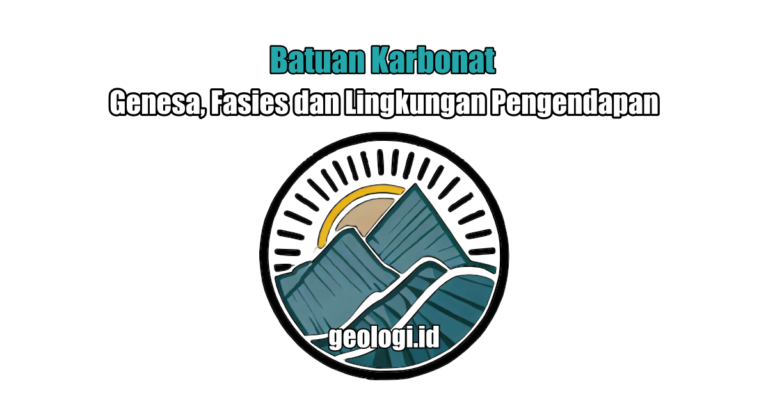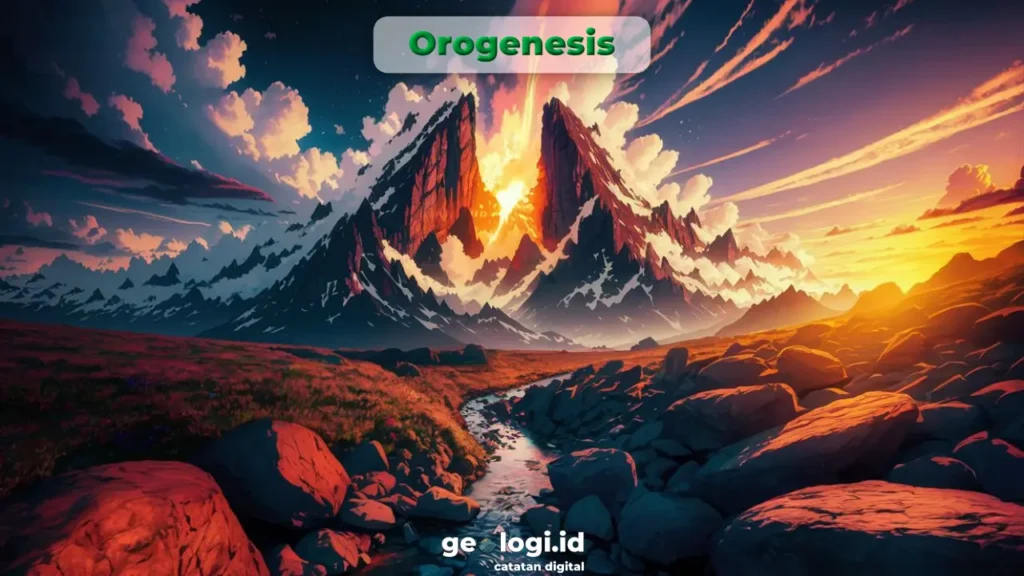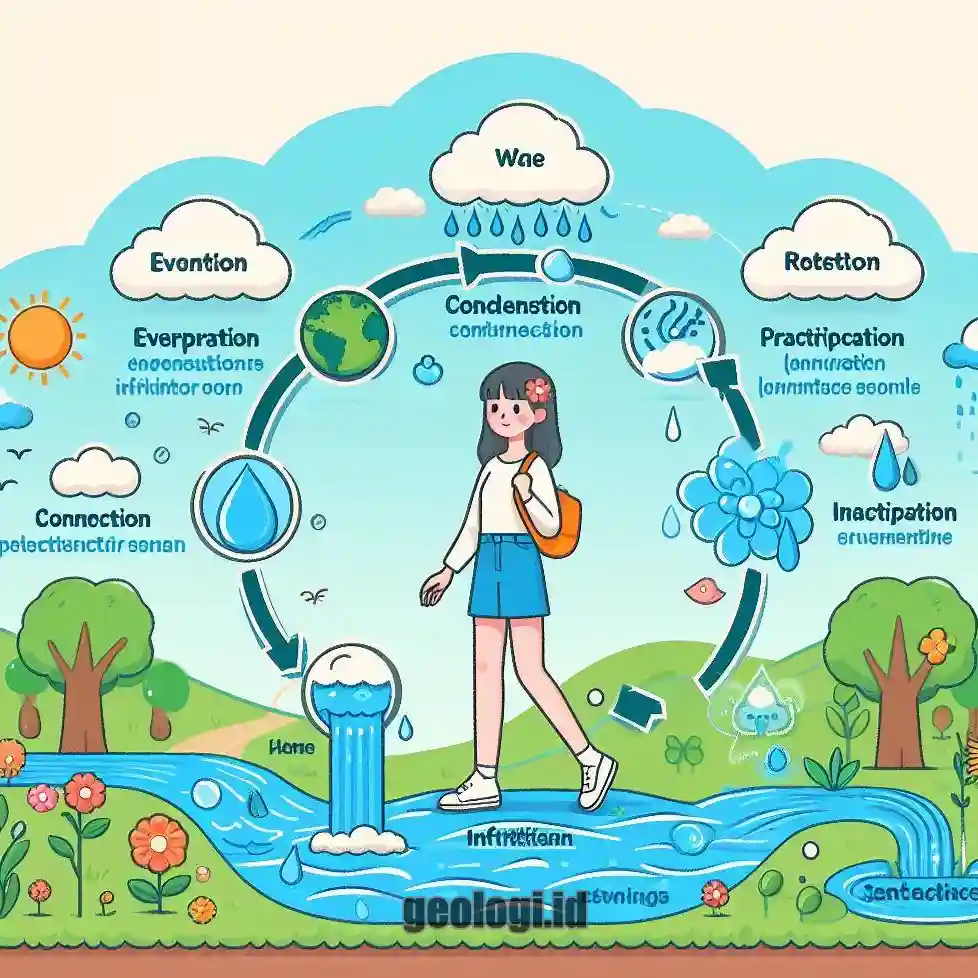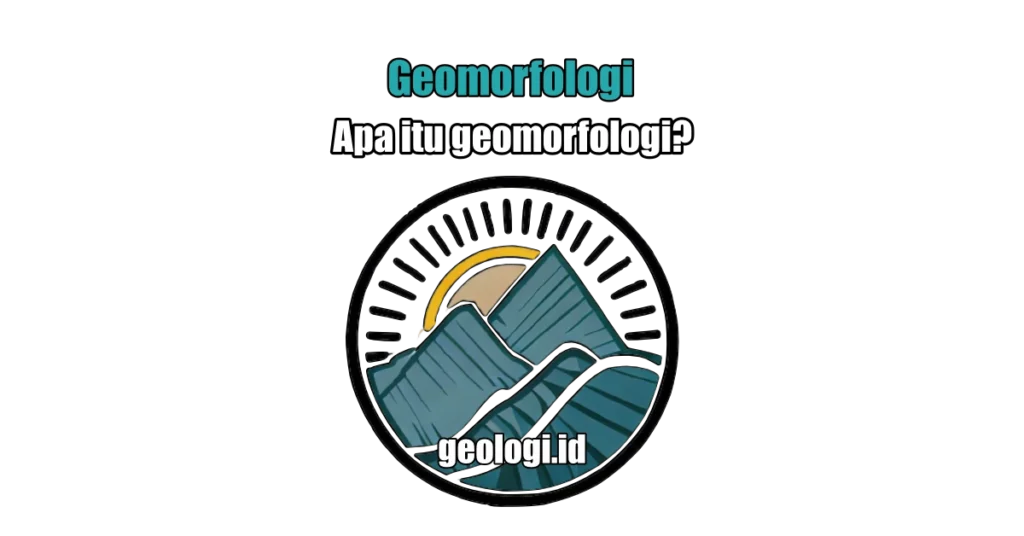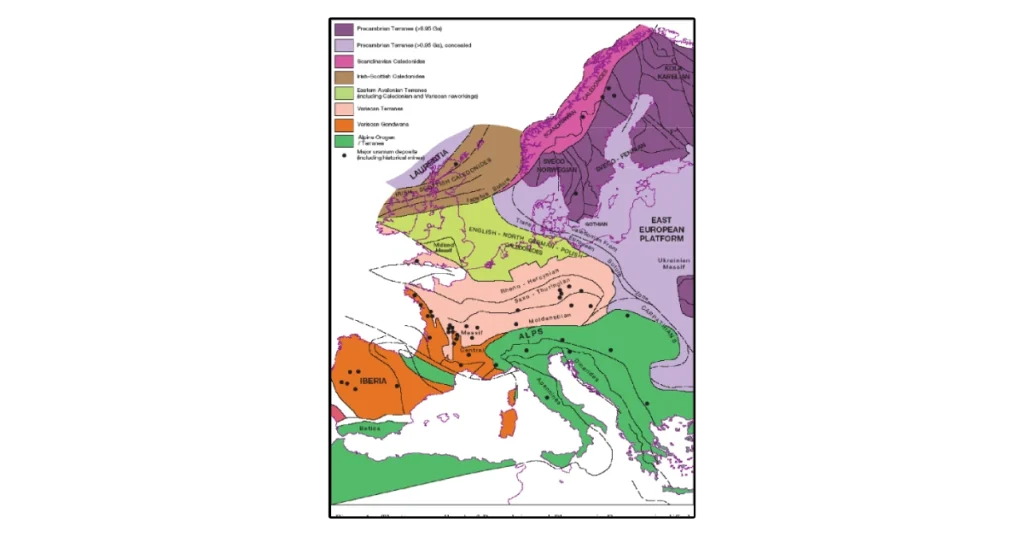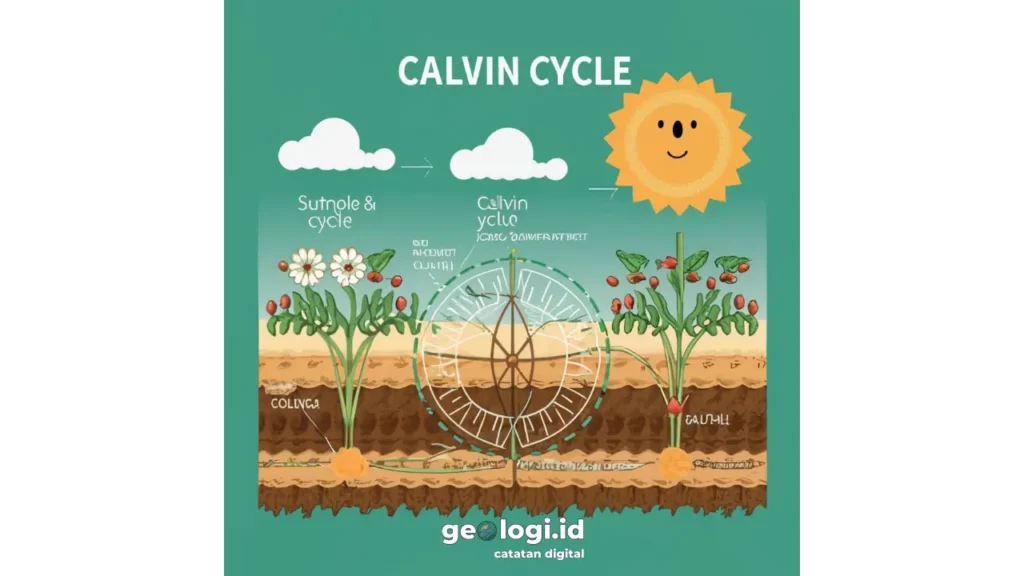Halo, sobat geologi! Apa kabar? Semoga sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas tentang batuan karbonat, yaitu salah satu jenis batuan sedimen yang terbentuk dari endapan organik atau anorganik yang mengandung karbonat. Batuan karbonat ini sangat penting dalam geologi, karena banyak mengandung fosil-fosil yang bisa memberi informasi tentang sejarah bumi dan kehidupan di masa lalu. Selain itu, batuan karbonat juga berpotensi sebagai sumber energi, seperti minyak dan gas bumi, serta sumberdaya mineral, seperti batu kapur dan marmer.
Nah, untuk mempelajari batuan karbonat ini, kita perlu mengetahui tentang genesa, fasies, dan lingkungan pengendapannya. Apa itu genesa, fasies, dan lingkungan pengendapan? Bagaimana cara mengenali dan membedakannya? Dan apa contoh-contohnya di Indonesia? Yuk, kita simak penjelasannya di artikel ini!
Genesa Batuan Karbonat
Genesa adalah proses terbentuknya suatu batuan dari bahan asalnya. Genesa batuan karbonat adalah proses terbentuknya batuan karbonat dari endapan organik atau anorganik yang mengandung karbonat. Karbonat adalah senyawa kimia yang terdiri dari ion karbon (C) dan oksigen (O) yang berikatan dengan ion logam atau non-logam lainnya. Rumus umumnya adalah MCO3 atau M2CO3, di mana M adalah ion logam atau non-logam.
Endapan organik yang mengandung karbonat biasanya berasal dari organisme laut yang memiliki cangkang atau kerangka karbonat, seperti foraminifera, radiolaria, koral, moluska, brakiopoda, bryozoa, echinodermata, dll. Endapan anorganik yang mengandung karbonat biasanya berasal dari presipitasi kimia atau fisika dari larutan karbonat di air laut atau air tawar.
Faktor-faktor yang mempengaruhi genesa batuan karbonat antara lain:
- Iklim: iklim yang hangat dan kering menghasilkan evaporasi air laut yang meningkatkan konsentrasi larutan karbonat dan memicu presipitasi kimia. Iklim yang hangat juga mendukung pertumbuhan organisme laut yang memiliki cangkang atau kerangka karbonat.
- Biota: biota yang hidup di laut atau air tawar dapat memproduksi endapan organik yang mengandung karbonat melalui proses biokimia atau biofisika. Biota juga dapat mempengaruhi sifat fisik dan kimia dari endapan karbonat melalui aktivitas bioturbasi atau biodegradasi.
- Tektonik: tektonik dapat mempengaruhi bentuk dan kedalaman dasar laut atau dasar air tawar yang merupakan tempat pengendapan karbonat. Tektonik juga dapat mempengaruhi sirkulasi air laut atau air tawar yang berhubungan dengan suplai nutrien dan oksigen bagi biota.
- Diagenesis: diagenesis adalah proses perubahan fisik dan kimia pada endapan sedimen setelah terbentuk menjadi batuan. Diagenesis dapat mempengaruhi tekstur, struktur, komposisi mineral, porositas, permeabilitas, dan warna dari batuan karbonat.
Contoh-contoh batuan karbonat yang terbentuk dari berbagai genesa antara lain:
- Batugamping terumbu: batuan karbonat yang terbentuk dari endapan organik yang berasal dari koral dan organisme lain yang hidup di lingkungan terumbu karang. Batugamping terumbu memiliki tekstur boundstone (terikat oleh matriks organik) atau grainstone (terdiri dari butiran karbonat), struktur biostrom (lapisan tipis) atau bioherm (bentuk gundukan), komposisi mineral kalsit atau aragonit, porositas dan permeabilitas tinggi, dan warna putih atau abu-abu. Contoh batugamping terumbu di Indonesia adalah di Pulau Weh, Aceh.
- Kalkarenit: batuan karbonat yang terbentuk dari endapan anorganik yang berasal dari presipitasi kimia atau fisika dari larutan karbonat di air laut. Kalkarenit memiliki tekstur grainstone (terdiri dari butiran karbonat), struktur laminasi (lapisan tipis) atau cross-bedding (lapisan miring), komposisi mineral kalsit, porositas dan permeabilitas rendah, dan warna putih atau abu-abu. Contoh kalkarenit di Indonesia adalah di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.
- Napal: batuan karbonat yang terbentuk dari endapan organik yang berasal dari mikrofosil planktonik yang hidup di lingkungan laut dalam. Napal memiliki tekstur wackestone (terdiri dari butiran karbonat halus yang dikelilingi oleh matriks halus) atau packstone (terdiri dari butiran karbonat halus yang dikelilingi oleh matriks kasar), struktur massive (tidak berlapis) atau nodular (berbentuk gumpalan), komposisi mineral kalsit atau dolomit, porositas dan permeabilitas rendah, dan warna abu-abu atau coklat. Contoh napal di Indonesia adalah di Cekungan Kutai, Kalimantan Timur.
Fasies Batuan Karbonat
Fasies adalah kesatuan batuan yang memiliki ciri-ciri fisik dan biologis yang khas dan berbeda dengan batuan lain di sekitarnya. Fasies batuan karbonat adalah kesatuan batuan karbonat yang memiliki ciri-ciri makroskopis dan mikroskopis yang khas dan berbeda dengan batuan karbonat lain di sekitarnya.
Kriteria pengelompokan fasies batuan karbonat antara lain:
- Tekstur: tekstur adalah susunan ukuran, bentuk, dan hubungan antara butiran atau kristal dalam suatu batuan. Tekstur batuan karbonat dapat dibedakan menjadi:
- Klastik: tekstur yang terdiri dari butiran karbonat yang berasal dari erosi atau fragmenasi batuan karbonat lain.
- Non-klastik: tekstur yang terdiri dari kristal karbonat yang berasal dari presipitasi kimia atau fisika.
- Bioklastik: tekstur yang terdiri dari butiran karbonat yang berasal dari organisme laut yang memiliki cangkang atau kerangka karbonat.
- Struktur: struktur adalah susunan lapisan, retakan, lipatan, atau bentuk lain dalam suatu batuan. Struktur batuan karbonat dapat dibedakan menjadi:
- Laminasi: struktur yang terdiri dari lapisan tipis (< 1 cm) yang berbeda warna, tekstur, atau komposisi.
- Bedding: struktur yang terdiri dari lapisan tebal (> 1 cm) yang berbeda warna, tekstur, atau komposisi.
- Cross-bedding: struktur yang terdiri dari lapisan miring yang menunjukkan arah angin atau arus air saat pengendapan.
- Biostrom: struktur yang terdiri dari lapisan tipis (< 10 cm) yang mengandung organisme laut seperti koral, bryozoa, dll.
- Bioherm: struktur yang terdiri dari bentuk gundukan (> 10 cm) yang mengandung organisme laut seperti koral, bryozoa, dll.
- Stromatolit: struktur yang terdiri dari lapisan tipis (< 1 cm) yang mengandung mikroorganisme seperti sianobakteri, alga, dll.
- Ooid: struktur yang terdiri dari butiran bulat (< 2 mm) yang mengandung lapisan-lapisan konsentris karbonat.
- Peloid: struktur yang terdiri dari butiran tidak beraturan (< 2 mm) yang – mengandung matriks organik atau anorganik yang berasal dari endapan lumpur atau pasir.
- Intraclast: struktur yang terdiri dari butiran pecahan (< 2 cm) yang berasal dari erosi atau fragmenasi batuan karbonat lain.
- Breksia: struktur yang terdiri dari butiran pecahan (> 2 cm) yang berasal dari erosi atau fragmenasi batuan karbonat lain.
- Komposisi mineral: komposisi mineral adalah jenis-jenis mineral yang menyusun suatu batuan. Komposisi mineral batuan karbonat dapat dibedakan menjadi:
- Kalsit: mineral karbonat yang memiliki rumus kimia CaCO3 dan kristal berbentuk romboid.
- Aragonit: mineral karbonat yang memiliki rumus kimia CaCO3 dan kristal berbentuk jarum atau tabular.
- Dolomit: mineral karbonat yang memiliki rumus kimia CaMg(CO3)2 dan kristal berbentuk romboid.
- Siderit: mineral karbonat yang memiliki rumus kimia FeCO3 dan kristal berbentuk romboid atau sferoid.
- Ankerit: mineral karbonat yang memiliki rumus kimia Ca(Fe,Mg,Mn)(CO3)2 dan kristal berbentuk romboid.
Klasifikasi fasies batuan karbonat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa sistem, seperti sistem Dunham, sistem Folk, sistem Embry dan Klovan, dll. Sistem Dunham mengelompokkan fasies batuan karbonat berdasarkan tekstur dan struktur, sedangkan sistem Folk mengelompokkan fasies batuan karbonat berdasarkan tekstur dan komposisi mineral. Sistem Embry dan Klovan mengelompokkan fasies batuan karbonat berdasarkan lingkungan pengendapannya.
Contoh-contoh fasies batuan karbonat yang ditemukan di Indonesia antara lain:
- Boundstone: fasies batuan karbonat yang terdiri dari matriks organik yang mengikat butiran-butiran karbonat. Boundstone biasanya terbentuk di lingkungan terumbu karang, seperti di Formasi Baturaja di Cekungan Sumatra Selatan. Boundstone memiliki tekstur bioklastik, struktur biostrom atau bioherm, komposisi mineral kalsit atau aragonit, porositas dan permeabilitas tinggi, dan warna putih atau abu-abu.
- Rudstone: fasies batuan karbonat yang terdiri dari butiran-butiran karbonat besar (> 2 mm) yang bersentuhan langsung tanpa matriks. Rudstone biasanya terbentuk di lingkungan fore reef, seperti di Formasi Parigi di Cekungan Jawa Barat Utara. Rudstone memiliki tekstur bioklastik atau klastik, struktur massive atau nodular, komposisi mineral kalsit atau dolomit, porositas dan permeabilitas rendah, dan warna abu-abu atau coklat.
- Grainstone: fasies batuan karbonat yang terdiri dari butiran-butiran karbonat kecil (< 2 mm) yang bersentuhan langsung tanpa matriks. Grainstone biasanya terbentuk di lingkungan open shelf, seperti di Komplek Kromong di Cekungan Jawa Timur. Grainstone memiliki tekstur bioklastik, non-klastik, atau klastik, struktur laminasi atau cross-bedding, komposisi mineral kalsit atau dolomit, porositas dan permeabilitas sedang, dan warna putih atau abu-abu.
- Packstone: fasies batuan karbonat yang terdiri dari butiran-butiran karbonat kecil (< 2 mm) yang dikelilingi oleh matriks kasar. Packstone biasanya terbentuk di lingkungan back reef, seperti di Formasi Parigi di Cekungan Jawa Barat Utara. Packstone memiliki tekstur bioklastik, non-klastik, atau klastik, struktur massive atau nodular, komposisi mineral kalsit atau dolomit, porositas dan permeabilitas rendah, dan warna abu-abu atau coklat.
- Wackestone: fasies batuan karbonat yang terdiri dari butiran-butiran karbonat halus (< 2 mm) yang dikelilingi oleh matriks halus. Wackestone biasanya terbentuk di lingkungan lagoon, seperti di Komplek Kromong di Cekungan Jawa Timur. Wackestone memiliki tekstur bioklastik, non-klastik, atau klastik, struktur massive atau nodular, komposisi mineral kalsit atau dolomit, porositas dan permeabilitas rendah, dan warna abu-abu atau coklat.
Lingkungan Pengendapan Batuan Karbonat
Lingkungan pengendapan adalah tempat atau kondisi dimana suatu batuan terbentuk dari endapan sedimen. Lingkungan pengendapan batuan karbonat adalah tempat atau kondisi dimana batuan karbonat terbentuk dari endapan organik atau anorganik yang mengandung karbonat.
Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendapan batuan karbonat antara lain:
- Kedalaman air: kedalaman air dapat mempengaruhi intensitas cahaya matahari, suhu, salinitas, tekanan, dan oksigen yang berpengaruh pada pertumbuhan organisme laut dan presipitasi kimia atau fisika karbonat.
- Arus air: arus air dapat mempengaruhi transportasi, pengendapan, dan erosi sedimen karbonat, serta suplai nutrien dan oksigen bagi organisme laut.
- Bentuk dasar air: bentuk dasar air dapat mempengaruhi sirkulasi, turbulensi, dan stabilitas air yang berpengaruh pada pertumbuhan organisme laut dan presipitasi kimia atau fisika karbonat.
Klasifikasi lingkungan pengendapan batuan karbonat dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa sistem, seperti sistem Wilson, sistem James, sistem Tucker, dll. Sistem Wilson mengelompokkan lingkungan pengendapan batuan karbonat berdasarkan bentuk dasar air, sedangkan sistem James dan Tucker mengelompokkan lingkungan pengendapan batuan karbonat berdasarkan kedalaman air.
Contoh-contoh lingkungan pengendapan batuan karbonat yang ditemukan di Indonesia antara lain:
- Restrict shelf: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan dangkal (< 50 m) yang terpisah dari laut lepas oleh hambatan seperti pulau atau terumbu. Restrict shelf memiliki sirkulasi air terbatas, salinitas tinggi, dan oksigen rendah. Restrict shelf menghasilkan endapan anorganik yang berasal dari presipitasi kimia atau fisika karbonat. Contoh restrict shelf di Indonesia adalah di Cekungan Sumatra Selatan, di mana terbentuk endapan evaporit seperti garam dan gipsum.
- Open shelf: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan dangkal (< 50 m) yang terhubung dengan laut lepas tanpa hambatan. Open shelf memiliki sirkulasi air bebas, salinitas normal, dan oksigen cukup. Open shelf menghasilkan endapan organik dan anorganik yang berasal dari pertumbuhan organisme laut dan presipitasi kimia atau fisika karbonat. Contoh open shelf di Indonesia adalah di Cekungan Jawa Timur, di mana terbentuk endapan kalkarenit dan grainstone.
- Fore reef: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan sedang (50 – 200 m) yang berbatasan dengan laut lepas oleh terumbu karang. Fore reef memiliki sirkulasi air kuat, salinitas normal, dan oksigen cukup. Fore reef menghasilkan endapan organik yang berasal dari erosi atau fragmenasi terumbu karang. Contoh fore reef di Indonesia adalah di Cekungan Jawa Barat Utara , di mana terbentuk endapan rudstone dan packstone.
- Reef core: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan dangkal (< 50 m) yang merupakan tempat tumbuhnya terumbu karang. Reef core memiliki sirkulasi air sedang, salinitas normal, dan oksigen cukup. Reef core menghasilkan endapan organik yang beras- al dari pertumbuhan koral dan organisme lain yang memiliki cangkang atau kerangka karbonat. Contoh reef core di Indonesia adalah di Pulau Weh, Aceh, di mana terbentuk endapan batugamping terumbu dan boundstone.
- Back reef: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan dangkal (< 50 m) yang berbatasan dengan daratan oleh terumbu karang. Back reef memiliki sirkulasi air lemah, salinitas normal, dan oksigen cukup. Back reef menghasilkan endapan organik dan anorganik yang berasal dari erosi atau fragmenasi terumbu karang dan presipitasi kimia atau fisika karbonat. Contoh back reef di Indonesia adalah di Cekungan Jawa Barat Utara, di mana terbentuk endapan packstone dan wackestone.
- Lagoon: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan dangkal (< 50 m) yang berada di antara terumbu karang dan daratan. Lagoon memiliki sirkulasi air terbatas, salinitas normal atau tinggi, dan oksigen rendah. Lagoon menghasilkan endapan organik dan anorganik yang berasal dari pertumbuhan mikroorganisme dan presipitasi kimia atau fisika karbonat. Contoh lagoon di Indonesia adalah di Cekungan Jawa Timur, di mana terbentuk endapan wackestone dan stromatolit.
- Tidal flat: lingkungan pengendapan batuan karbonat yang terletak di perairan sangat dangkal (< 10 m) yang berada di dekat pantai dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Tidal flat memiliki sirkulasi air bergantung pada siklus pasang surut, salinitas normal atau tinggi, dan oksigen rendah. Tidal flat menghasilkan endapan anorganik yang berasal dari presipitasi kimia atau fisika karbonat. Contoh tidal flat di Indonesia adalah di Cekungan Sumatra Selatan, di mana terbentuk endapan kalkarenit dan ooid.
Penutup
Demikianlah artikel ini membahas tentang batuan karbonat, yaitu salah satu jenis batuan sedimen yang terbentuk dari endapan organik atau anorganik yang mengandung karbonat. Kita telah mempelajari tentang genesa, fasies, dan lingkungan pengendapan batuan karbonat, serta contoh-contohnya di Indonesia.
Semoga artikel ini bermanfaat bagi Anda yang ingin menambah wawasan tentang geologi, khususnya tentang batuan karbonat. Jika Anda memiliki pertanyaan, saran, atau kritik, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah membaca artikel ini sampai habis. Sampai jumpa di artikel selanjutnya!
: Formasi Baturaja : Formasi Parigi : Stratigrafi Cekungan Jawa Barat Utara : Komplek Kromong : Cekungan Sumatra Selatan : Cekungan Jawa Timur : Cekungan Kutai